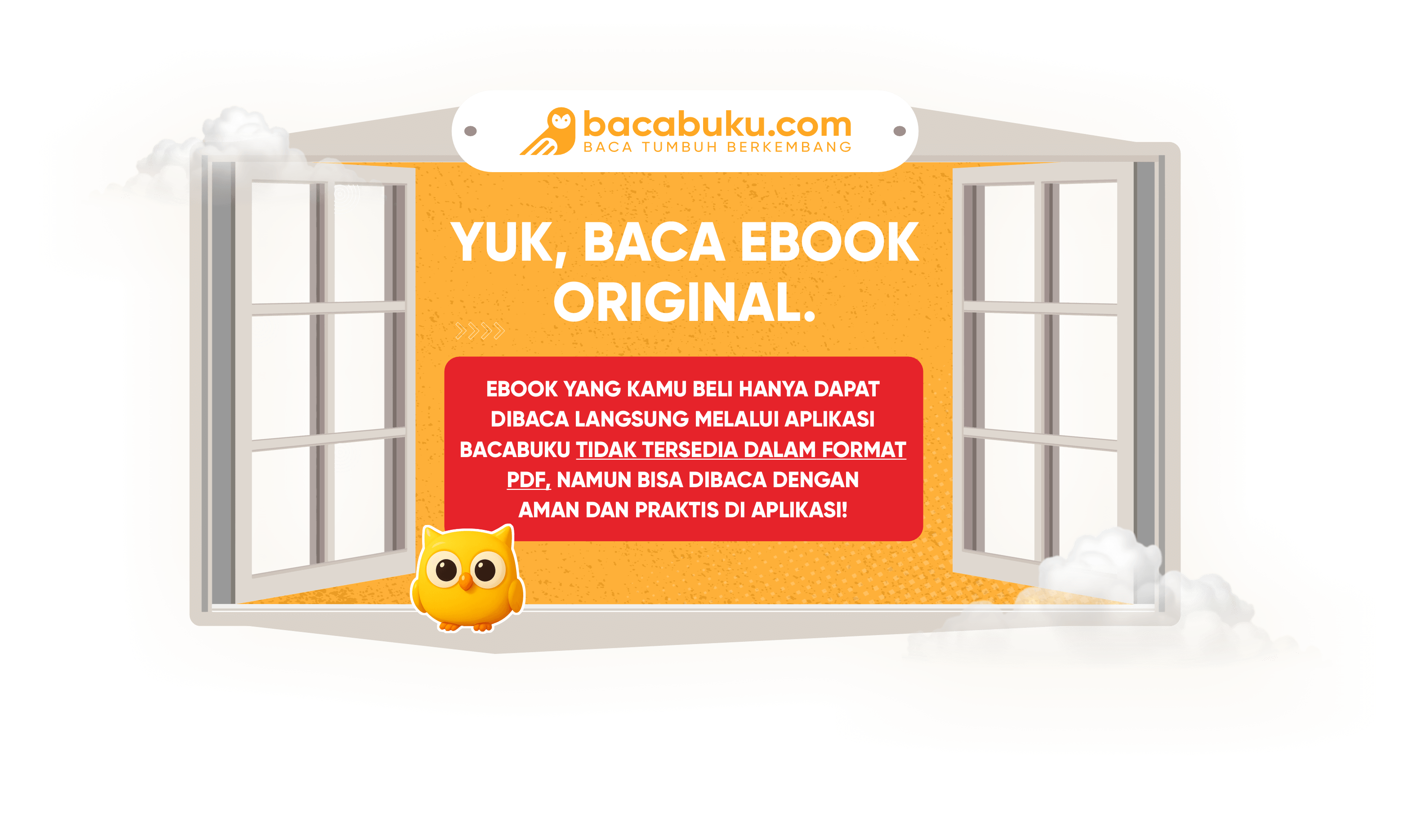- Beranda
-
Dialog Dengan Kiai Ali Yafie

RELIGION & SPIRITUALITY
Dialog Dengan Kiai Ali Yafie
Sinopsis
“Jika kaum muslimin mengklaim agamanya sebagai agama yang shalihah li kulli zaman wa makan dan rahmatan lil ‘alamin, “ Tanya Renan, seorang sarjana Eropa terkemuka , kepada Syekh Muhammad Abduh, “maka tunjukkan kepadaku bukti empirisnya, negara mana?” Dan Muhammad Abduh tidak sanggup menjawab pertanyaan ini. Kenapa pasal? Ada sejumlah problem besar yang masih menghinggapi kaum muslimin hingga hari ini. Salah satnya, sumber-sumber pengetahuan keagamaan masih merupakan produk pemikiran atau ijtihad kaum muslim abad pertengahan dalam nuansa Arabia. Sementara, hidup terus bergulir, berubah, dan berganti. Dokumen aturan yang dibuat pada masa lalu secara tekstual dan rigid itu tak lagi maslahah (relevan) menghadapi realitas baru, bahkan bias membebani dan menyulitkan. Lantas, apa saja jalan keluar bagi kemandekan kebudayaan bangsa-bangsa muslim tersebut? Jawabannya: menghidupkan cahaya akal. Mengapa harus akal? Andai kata tanpa akal, tutur Imam Ghazali, niscaya kenabian dan syariat (hukum-hukum) tidak dapat dipahami. Orang yang akal pikirannya tidak terbuka, maka ia hanya memahami agama dari kulitnya, bahkan berdasarkan khayalan dan sejenisnya (ilusi), bukan saripati dan substansinya. Selain tentang peran akal, banyak hal yang dibahas di buku yang memuat dialog Kiai Husein dengan Kiai Ali Yafie ini. Misalnya, tentang Pancasila dan ajaran Islam, HAM, Negara-Bangsa, dan lain sebagainya.
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
Unduh untuk perangkat lain:
Ulasan Pembaca
Ulasan (0)

Belum Ada Ulasan
Jadilah yang pertama memberikan ulasan!
Bukunya bagus banget!
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam nulla iusto repellat qui, soluta laborum deserunt quis veritatis reprehenderit sint assumenda natus officiis! Nesciunt nisi eius rem dolor placeat consectetur.
Isinya daging semua cuy! Recomended.